Perbandingan waktu antara Jakarta dan Singapura adalah satu
jam. Pesawat mendarat jam 13.30 WIB atau jam 14.30 waktu bagian Singapura. Jika
kami berangkat pagi, seharusnya kami sudah sampai sekitar jam 10.20 waktu
setempat. Meski demikian, aku bersyukur dan tersenyum lebar karena akhirnya
sampai dengan selamat meski ada insiden konyol sebelumnya. Bersih, adalah kesan
pertama saat kaki menginjakkan Bandara Cangi. Walau aku yakin pasti di sudut
lain juga bersih, tetapi aku ingin memastikan bahwa negara maju memperhatikan
kebersihan toiletnya. Aku sering mengeluh dengan kotornya toilet umum di
Indonesia, bahkan di tempat wisata. Aku mempunyai penilaian bahwa apabila
toilet di suatu tempat bersih, maka pemiliknya memang benar-benar memperhatikan
kebersihan secara keseluruhan. Bersih, tertata, dan modern. Begitulah keadaan
toilet bandara ini. Oke, berarti memang benar. Sayangnya, ada satu hal yang
sangat tidak cocok bagi orang Indonesia, khususnya bagi umat Muslim. Apa itu?
Tidak ada air di dalam toilet! Toilet di bandara ini memang memakai dry system, jadi ya cuma ada tisu di
toiletnya. Waduh, irit air
atau kelewat western ya?
Setelah dari toilet, kami menunggu skytrain yang disediakan gratis untuk menuju terminal 2. Sebenarnya
kami hanya asal mengikuti rombongan penumpang sepesawat dengan kami. Kalau di
Soe-Ta biasanya disediakan bus. Kecanggihan negeri ini mulai menyapa dari sini.
Aku bertemu dengan dua biro perjalanan yang membawa rombongan jamaah umroh dari
Lombok. Wajah mereka yang Indonesia sekali langsung dapat kukenali. Sepertinya
mereka city tour terlebih dahulu
sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab. Sekitar 10 menit kereta yang berjalan
otomatis itu tiba, sayangnya cuma ada tempat duduk prioritas untuk orang tua,
ibu hamil, anak-anak, dan difable sehingga kebanyakan penumpang hanya bisa
berdiri.
Tanggal 28 Januari kemarin baru saja ada perayaan Imlek,
sehingga ada satu taman bunga di salah satu sudut terminal 2 yang dilengkapi
dengan patung-patung ayam sesuai dengan nama tahun Imlek tahun ini
 |
| Nuansa Imlek |
Sebelum melewati petugas imigrasi, kami harus menulis data
pribadi terlebih dahulu di selembar kertas, meja, dan pena yang disediakan
bandara. Kami saling tanya dengan pengunjung lain jika ada pertanyaan yang
tidak mengerti. Selesai mengisi, kami mengantri di bagian imigrasi. Antrian ini
seperti ular naga yang panjangnya bukan kepalang. Maklum saja Cangi adalah salah
satu bandara tersibuk di dunia. Bule, Cina, Melayu, Negro terlihat dalam
antrian ini termasuk para Jemaah umroh dari Lombok tadi yang mengantri di
sebelahku. Banyak mata memandang ke arah mereka yang kebanyakan kakek-kakek dan
nenek-nenek. Pandangan mereka seperti bertanya-tanya dari mana mereka? Mau apa?
Mengapa berseragam begitu? Wajar saja, penampilan mereka begitu mencolok di
antara pengunjung yang berpenampilan serba kekinian (ngartis, sexi, tatanan
rambut salon, barang-barang brandid,
dsb): kemeja batik panjang dengan peci untuk sebagian jemaah laki-laki dan jilbab
untuk perempuan. Terdapat satu dua jemaah perempuan yang celana panjang
dalamannya yang berwarna-warni melebihi panjang roknya, ada juga nenek-nenek
yang terlihat dingin saja berada di bandara mewah ini, tidak seperti aku yang
sedari tadi merasa terkesan dengan kecanggihan dan kebersihannya. Bayangan
kebesaran Makah yang lebih mengagumkan dan dinantinya selama bertahun-tahun
telah mengendap di pikiran dan batinnya.
Ketua rombongan jemaah meminta kepada petugas untuk
didahulukan. Barangkali karena ada banyak orang tua dan juga mereka mengejar
waktu sebelum berangkat ke tanah suci. Hem, andaikan aku bisa menyelinap
bersama mereka. Aku merasa megantri lama sekali. Sepertinya aku berada di barisan
20an. Jika per orang membutuhkan waktu 5 menit, silakan dikalikan saja dengan
20 orang. Hufht… kuletakkan ranselku di lantai. Tips menggembel nomor 4:
tulislah data diri sambil mengantri di imigrasi Cangi untuk mempercepat waktu.
Waktu menunjukkan jam 16.00. Aku belum sholat Zuhur dan
Ashar. “Tenang saja, Ashar di sini jam 4 dan aku sudah download waktu solat di Singapura.” Kata Miss Lisfah sambil
menunjukkan foto download nya di
smartphone. Dahiku sedikit mengerut melihat layarnya. “2016?” tanyaku. “Ya
Allah…aku salah download. Yah,
semestinya sih nggak jauh beda dengan ini.” Jawabannya masuk akal.
Kadang orang khawatir tidak diizinkan melewati batas imigrasi
oleh petugas. Batas imigrasi ini seperti pintu masuk dari luar ke dalam rumah
orang. Jika mencurigakan bisa saja pengunjung ditahan. Isu terorisme yang
dikaitkan dengan agama Islam atau asal negara yang paling sering menjadi
alasannya. Tapi nyatanya aku dengan segala atribut keislamanku sama sekali tak
membuat petugas imigrasi curiga apalagi melarang masuk.
“Kita harus beli kartu multi trip untuk naik kereta.” Ajak
Miss Lisfah setelah menukarkan rupiah menjadi dolar Singapura yang menjadi
beberapa lembar saja. Pada saat itu 1 SGD seharga RP 9.300,00 dan aku menukar
sebanyak Rp 2000.000,00. Aku berusaha untuk mencukupkan uang sebanyak itu
sampai pulang dari Malaysa, kalau bisa masih ada kelebihannya. Luruskan tujuan
sampai akhir bahwa aku di sini bukan untuk wisata shoping.Masih di sekitar money
changer, ada sebuah stand yang menjual kartu multi trip.
“12 SGD per card.” Kata embak yang jaga. Ini pengeluaran pertamaku di Singapura yang termasuk banyak karena jika kita beli kartu Trans Jakarta (TJ) cukup membayar Rp 40.000,00 saja. Andaikan aku bisa memakai kartu TJ ku di sini.
“Oke, sekarang kita cari Musola.” Ajakku
“Di sini ada nggak ya?”
“It’s an international airport. I’m sure it has. Pasti adalah.” Aku yakin meski dari tadi aku tak melihat ada tulisan prayer room
Terlihat dua orang yang clingukan (it means kebingungan in Bahasa Indonesia), seorang petugas menanyai kami, “What are you looking for?”
“Where is the prayer room?” Miss Lisfah menjawab dengan sebuah pertanyaan
“Prayer room?” dia malah balik bertanya.
“Yes, we need to pray.”
“Em… in this building? Sorry we don’t have that in this building. But maybe you can find in the outside.”
What? I don’t believe
that! Bagaimana bisa
bandara modern, canggih, dan sibuk luar biasa begini tak memiliki seruang
Musola? Usut punya usut aku baru tahu bahwa Musola di terminal 2 ada di dekat
transit area lantai 2. Itu artinya kami harus ke prayer room sebelum mengantri ke immigration check point. Sayangnya petugas tidak menyampaikan
detail tempatnya, tapi kalaupun diberitahu kami tak mungkin masuk lagi.
“Oke, kita cari di luar.” Ajakku pada Miss Lisfah sambil
berjalan meninggalkan bandara. Kami tidak terpikirkan untuk berkeliling di
bandara karena kami mengejar waktu Sholat. Dalam pikiranku aku hanya ingin
Sholat, mandi, dan makan. Cukup. Urusan berkeliling nanti setelah ketiganya
terpenuhi. Kami berpikir setidaknya mendapat roti di pesawat, ternyata tidak
sama sekali.
Kartu multi trip harus di tap dahulu sebelum masuk stasiun.
Tertera $7, berarti harga kartunya sendiri sebanyak $5. Bandara di Cangi memang
terhubung dengan MRT segala arah dan salah satu tujuannya bisa langsung menuju
halte bus dekat dengan hostel kami. Kami memilih tujuan ke Bugis.
Tak lama kemudian MRT datang. Lengang. MRT ini di atas level KRL di
Jakarta. Yang pasti lebih canggih, lebih aman dan lebih bersih. Disebut
lebih aman karena ada sekat kaca yang memisahkan kereta dengan penumpang yang
menunggu di stasiun, jadi tidak mungkin ada orang atau barang yang terjatuh di
tengah rel. KRL Jakarta hanya diberi garis kuning. Para penumpang
mengikuti peraturan dilarang makan dan minum di dalam kereta dengan baik,
meskipun tak ada polisi kereta. Kalau di Jakarta aku masih melihat satu dua
yang makan bahkan membuang bungkus permen di dalam KRL.
Kami harus transit ke Tanah Merah. Wah, kalau di Jakarta
namanya Tanah Abang. Abang dalam bahasa Jawa artinya merah. Jadi Tanah Merah
juga bisa berarti Tanah Abang. Lucu juga, ya? Apakah Tanah Merah ini seramai
Tanah Abang? Setelah kami naik MRT lagi dari Tanah Merah, pertanyaan itu
terjawab dengan kata “Ya”. Saking
ramainya, banyak penumpang tidak dapat tempat duduk, termasuk aku. Padahal
jarak dari Tanah Merah ke Bugis cukup jauh dan harus melewati 8 stasiun. Sayangnya, tidak ada orang yang mempersilakan
kusinya untukku.
Tak hanya soal keretanya yang berbeda dengan Jakarta, tetapi
orang-orangnya juga jelas berbeda. Sikap masyarakat cenderung lebih cuek dan
bebas, khususnya mereka yang ber etnis Tionghoa (maaf saya tidak bermaksud
rasis). Meski di Jakarta aku juga sering bertemu dengan etnis ini, tetapi cara
mereka berpenampilan cukup sopan. Kalau di sini, hem… I saw so many sexi girls and women dan terlihat beberapa muda-mudi
yang sepertinya berpasangan mengobrol dan bersentuhan dengan mesra dan santai
meski banyak mata yang melihat mereka. OMG, saya sedang di negara baratkah?
Sekitar 40 menit kami sampai di pemberhentian Bugis. Aku belum
pernah ke Bugis sesungguhnya di Indonesia, tapi lucunya aku malah sampai di
Bugis Singapura. Sejak Mrs Aisya menyarankanku mencari hostel di daerah Bugis,
aku penasaran mengapa namanya Bugis. Mrs Aisya hanya mengatakan daerah itu
pusat Muslim, tetapi tidak menyampaikan kaitannya dengan Bugis di Indonesia.
Selama ini yang kutahu apabila ada nama tempat yang asing dengan wilayah
sekitarnya, berarti ada kaitan sejarah dengan nama asing itu. Seperti nama
Kabupaten Pring Sewu di Lampung yang ternyata daerah itu ditempati oleh
transmigran Jawa.
 |
| Bugis dan Pinisi di "Bugis" Singapura |
Wallaa…. Ini dia kota di Singapura, tepatnya di Victoria St.
Terlihat sangat berbeda dengan Jakarta. Banyak orang yang berjalan kaki, naik
mobil, atau transportasi umum. Aku tak melihat orang naik motor. Jalan raya
terlihat lebih sepi dan sempit.
 |
| Sepi |
Nyasar 1
“Nah, betul. Kita di Victoria Street. Berarti kita ke sana.”
Ucap Miss Lisfah sambil menunjuk ke kiri jalan. Aku mengikut saja karena memang
dia yang bertugas menulis tempat-tempat tujuan dan aku sama sekali tidak
membawa peta atau apapun yang berhubungan dengan how to get Sleepy Kiwi Hostel. Kami berjalan terus lalu menyeberang
perempatan jalan besar. Sampai akhirnya Miss Lisfah mengatakan lagi,
“Sepertinya hostel kita dibalik gedung itu. Kita harus menyeberang perempatan
tadi.” Ucapnya sambil melihat catatan kecil yang telah ditulisnya di Jakarta.
Setelah menyeberang, kami lanjutkan berjalan kaki ke arah
yang sama, yaitu ke selatan. Baru berjalan sekitar 7 menit, Miss Lisfah
berhenti sambil membuka lipatan peta Singapura yang didapatnya dari bandara.
“Sebentar, kita lihat peta dulu.” Momen ini kumanfaatkan dengan duduk di
pedestrian.
“Aku masih ada roti satu. Mau nggak? Tawarku pada Miss Lisfah yang maksudku silakan mengambil setengahnya. Dia lalu mengambil setengahnya seperti maksudku.
“Sepertinya kita harus berbalik arah. Kita salah jalan.”
“Hah? Masak?” respoku
“Iya. Kita harusnya ke Rochor Road.”
“Kita mau ke penginapan dulu atau ke Masjid Sultan dulu?” tanya Miss Lisfah
“Kayaknya kita ke Masjid dulu aja deh. Soalnya uda jam segini.”
“Habis naroh barang di hostel kita cari makan ya. Udah laper banget.”
Perutku yang sempat terisi sekotak susu coklat saja lapar,
apalagi dia yang sedari pagi hanya minum air putih dan satu setengah potong
roti. Saat di perempatan kami bertanya pada seorang bapak letak Masjid Sultan.
Kami jelaskan bahwa kami belum membeli kartu lokal, jadi kami tak bisa
mengakses internet. Ternyata beliau juga tidak tahu dan dengan senang hati
mencarikan lewat google map. Oh, ternyata Masjid itu ada di arah timur laut dan
sejak kami turun dari MRT kami berjalan ke arah barat daya.
Nyasar 2
Senangnya kami waktu akhirnya menemukan salah satu tempat tujuan. Misi 1 selesai! Seorang mas-mas duduk di serambi masjid, di depanya ada meja dengan gambar masjid di sisi depan, di sekitarnya ada sarung-sarung dan payung-payung yang digantung. Sepertinya dia seorang receptionist. Miss Lisfah bertanya padanya, “Do you know, where is Sleepy Kiwi Hostel?”
Senangnya kami waktu akhirnya menemukan salah satu tempat tujuan. Misi 1 selesai! Seorang mas-mas duduk di serambi masjid, di depanya ada meja dengan gambar masjid di sisi depan, di sekitarnya ada sarung-sarung dan payung-payung yang digantung. Sepertinya dia seorang receptionist. Miss Lisfah bertanya padanya, “Do you know, where is Sleepy Kiwi Hostel?”
“Em…I don’t know.” Jawabnya sambil geleng kepala
“Oh, ok, baiklah.”
“Trus, kita ke mana?” tanyaku padanya
“Kalau di catatanku, kita harus ke sana. Arab Street.” Telunjuknya mengarah ke utara.
Lalu kami berjalan ke jalan besar awal, menyeberang
perempatan ke arah utara. Tak seberapa lama, sambil melihat peta besar, Miss
Lisfah seperti menyadari sesuatu. “Sebentar, sepertinya kita salah jalan.”
“Hah? Masak? Trus ke arah mana?”
Ada ibu-ibu berpenampilan Melayu keluar dari sebuah toko.“Sorry, do you know Bussorah Street?” tanya Miss Lisfah
“Oh, adek lurus saja jalan ini. Belok kiri ada Baghdad Street, lurus saja nanti ada Bussorah Street.” Jelasnya dengan sangat yakin bahwa kami mengerti bahasa Melayu. Lagi-lagi kami berjalan berlawanan arah.
“Sepertinya aku yang harus baca peta.” Kataku pada Miss Lisfah sambil meminta peta yang sedari tadi dibawanya
“Sorry, aku memang tidak pandai membaca peta.” Jelasnya seperti merasa bersalah.
Lalu mengapa tidak sampaikan itu sejak awal? Batinku. Kami
mulai berjalan dengan percaya diri ke arah Baghdad Street yang terlihat banyak
sekali rumah makan kecil dengan bangunan kuno yang sebangun, hanya beda cat dan
pernak-pernik dekorasi. Suasananya seperti di sebuah kampung, tapi tertata dan
banyak aksen modern. Saat itu matahari sudah condong ke barat, hawa teduh dan
angin semilir membuat banyak turis asing bersantai di serambi rumah makan sambil
mengobrol asik.
Langkah kami terhenti di sebuah tanah lapang di perempatan
jalan. Tarik nafas sambil bertanya-tanya di mana hostel kami berada. “Bussorah Street, tempatnya di Bussorah Street. Kalau benar
berarti perempatan jalan tadi. Di mana ya?”
Miss Lisfah membuka pembicaraan dengan pertanyaan.
Hampir semua orang berkumpul di rumah makan, hanya satu dua
orang yang lewat. Sayangnya tidak ada satupun orang yang bertanya kepada kami, “May I help you?” Beban 9 Kg di ransel dan 1 Kg di tas
samping membuat pundakku cukup pegal setelah memanggulnya sejak di bandara.
Untung aku tidak tertarik menambah bawaan menggunakan koper. Betapa ribetnya
kalau aku membawanya.
“Begini saja, aku cari dulu di sekitar sini, kamu jagain
tasku.” Aku menawarkan diri untuk mencari hostel. Aku pikir cara ini lebih
efisien dan yang jelas mengurangi beban bawaan. Saranku diterima, jadi aku
berjalan kembali menuju tuisan Bussorah Street. Aku belok kiri dan berjalan lurus
di antara toko dan rumah makan. Ah, sepertinya bukan di area ini. Mana mungkin
ada penginapan di antara toko-toko kecil. Lagipula aku sama sekali tak meihat
tulisan Sleepy Kiwi. Langkahku terhenti sebelum aku melanjutkan hingga ujung
jalan, lalu berjalan berbalik arah di sepanjang jalan Bussorah Street bagian
timur. Semakin tak meyakinkan karena jalanan sepi. Hhhh…Ini seperti permainan
mencari harta karun memakai peta yang berisi teka-teki. Aku mengelilingi
jalan-jalan kecil dan menuju di titik semula. Lagi-lagi bertemu ibu-ibu
berpenampilan Melayu, “Excuse me, do you
know Sleepy Kiwi Hostel?”
“No, I don’t know.” Jawabnya sambil geleng-geleng. Apa ini hostel baru ya, sampai-sampai 2 orang yang ditanya jawabnya selalu tidak tahu.
“Do you know Bussorah Street?”
“Oh, you should walk there. It is there, but I don’t know Sleepy Kiwi.” Ibu itu menunjuk arah yang sudah aku lewati tadi, tapi aku tidak yakin di sana ada sebuah hostel.
Aku kembali ke
titik semula dan gantian Miss Lisfah yang mencari. Beberapa saat kemudian,
sambil membawa sebotol air mineral dingin dan wajah sumringah, dia kembali
sambil berkata, “Di sana-di sana. Hostelnya ada di sana.” Sambil menunjuk arah
tempatku berjalan tadi. Dan…Arghh….hostel kecil itu hanya terpaut beberapa
bangunan dari pintu masuk Masjid Sultan tempat kami masuk dan keluar tadi.
“Astagaaaaaa…… ternyata hanya di sini! Aku tadi juga sudah ke sini tapi ragu, jadi balik arah. Ya ampuuunnn….dekat sekali dengan Masjid. Kenapa kita tadi berputar-putar?” perasaanku antara senang dan gemas sekali.
“Iya, ya..ya Allah...ternyata deket banget sama masjidnya.”
“Ih, sebel banget deh ternyata sedekat ini. Kenapa penjaga masjid tadi nggak tau ya?”
Aku jadi merasa saking banyaknya turis dan pendatang di area
ini, mereka tidak tahu letak tempat secara detail atau mungkin karena terlalu
dinamisnya tempat ini, toko dan rumah makan yang tak dapat berinovasi cepat
tergantikan oleh yang lain sehingga orang tidak tahu nama-nama toko atau hostel
baru. Sewaktu aku di Papua, orang sekampung pasti tahu letak Jalan Julius Tawer
karena itu satu-satunya nama jalan di kampung. Bahkan rumah setiap orang pun
mereka tahu.Tips meggembel no 5: pastikan lokasi tujuan sebelum
berangkat, apalagi jika tidak punya kartu lokal. Screen shoot petanya dan jangan malas bertanya.
Waktu check in
pemiliknya langsung mengerti saat kusebutkan namaku. Dia hanya minta
ditunjukkan paspor. Namanya juga hostel, jadi penampilannya santai sekali
seperti orang rumahan. Kaos tanpa lengan, jeans selutut, dan sandal jepit.
Rambut gondrong sebahunya terurai dan lengan kanannya penuh tato, tapi dia
menunjukkan keramahannya. Kami diantar ke kamar yang berisi 14 kasur. Semua
tepat seperti dalam pesanan.
Kami hanya meletakan tas di hostel, lalu ke masjid lagi
karena terdengar adzan Mahgrib. Waah..senangnya kami dapat mendengar adzan dari
negara asing yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Cara imam mengingatkan
jemaah sebelum solat dan mengisi ceramah sesesai solat pun mirip dengan
Indonesia, hanya saja beliau memakai bahasa Melayu. Arsitektur bangunan Masjid
ini terkesan klasik. Aku sangat, sangat bersyukur akhirnya bisa menapakkan
kakiku di negara asing dan lebih bersyukur lagi karena bagunan pertama yang
kutapak adalah masjid. Aku dengan cepat merasa seperti di masjid kampung
sendiri. Selesai sholat, kami ambil foto-foto sebentar
dengan keadaan yang super natural: lelah, lapar, haus, muka kucel, dan belum
mandi sejak pagi. Kalau saja perutku tidak meronta minta diisi, aku ingin berlama-lama
di masjid ini sampai Isya.
Di sebelah barat masjid terdapat banyak semacam warung
makanan halal. Para pekerjanya berbadan tinggi, berhidung mancung, dan berkulit
gelap. Menu makanannya macam-macam Murtabak dan Kari. Semua menegaskan bahwa ini warung makan halal ala
India. Oke, I’ll try, tapi yang tidak
terlalu asing. Pelayannya yang super ramah. Lagi-lagi tanpa bertanya terlebih
dahulu, beliau bertanya menu pakai bahasa Melayu. Kami memilih Murtabak daging
sapi small size seharga $5 dibagi
berdua ditambah es teh lemon $1,5. Sebenarnya kami melihat banyak makanan khas
Indonesia di sekitar hostel, seperti rumah makan Minang hingga penyet-penyetan
ala Jawa Timur, tapi rasanya lucu saja jauh-jauh ke Singapura yang dimakan
makanan Indonesia.
“Uncle, kenapa bisa bahasa Melayu?” tanyaku yang malah membuat dahinya berkerut.
“Tak mengerti.” Jawabnya. Sepertinya beliau tak paham pertanyaanku. Seorang perempuan muda di sebelahku menerjemahkan pertanyaanku ke bahasa Melayu yang langsung dipahaminya.
“Oh, saya orang Malaysia. Pindah ke sini untuk bekerja. Awak orang mana?”
“Saya Indonesia.”
“Oh, saya tahu-tahu sikitlah bahasa Indonesia karena banyak juga orang Indonesia ke sini.” Saya ke sana dulu ya.”
Keramahannya terpotong karena harus melayani pembeli lain.
Warung ini memang laris sekali. Selain karena harganya cukup murah untuk
seharga Singapura, lokasinya juga di daerah turis asing berkantong backpacker. Nyes…nyes…nyes…es teh lemon yang dingin dan segar membasahi
tenggorokan yang kering. Kalau dihitung-hitung, $5 dibagi berdua jadi $2,5
masih dibagi lagi menjadi 3 karena sarapan dan makan siang dirapel di makan
malam. Jadinya $0,83 alias Rp 7.749,00. Wow, murah sekali makan malam hari ini.
 |
| Es Jeruk Nyes2 |
 |
| Sepiring berdua=IRIT |
“Hemat sekali makan malam kita. Hahah.” Kutunjukkan hitungan konyolku pada Miss Lisfah
“Ya tapi kalau harus nggak makan dari pagi aku nggak mau. Itu namanya pelit sama diri sendiri.”
“Hahahaha…”
Oke, hari pertama ditutup dengan tidur nyenyak setelah perut
kenyang, berkeliling di sekitar Masjid setelah Solat Isya, mengolesi kaki
dengan minyak urut yang efek baunya bisa menyebar ke seluruh ruangan, dan yang
jelas guyuran air dari shower.
***
Jam 5 pagi kami ke masjid untuk siap-siap Sholat Subuh.
Sekitar hampir jam 6 Sholat Subuh baru dimulai. Tidak ada kultum di masjid ini.
Suasana masih sangat sepi dan gelap. Jam 7.30 barulah beberapa orang terlihat
berlalu-lalang. Wah… padahal kalau di Jakarta jam 5 pagi saja sudah banyak
orang berangkat ke kantor. Barangkali ini karena matahari datang agak terlambat
dibanding Indonesia dan tidak banyak orang yang bangun pagi untuk beribadah,
sehingga aktivitas mereka pun dimulai beberapa jam setelah kita.
Sambil menunggu sarapan disediakan hostel, kami mengobrol
dengan dua mas-mas penghuni hostel yang juga orang Indonesia. Mereka ada
keperluan bisnis di Singapura. Mereka juga berpendapat sama denganku tentang
suasana pagi ini, sepi. Aku juga sempat beberapa kali mengambil foto di sekitar
jalan Bussorah ini.
 | |
| Di depan Hostel, Jam 7 pagi pun masih sepi |
 |
| Arsitektur hostel yang klasik |
Sebuah papan bergaya etnik keJawa-jawaan menyedot
perhatianku. Papan yang terpasang di dekat hostel itu lalu mengejutkanku karena
cerita yang tertulis di sisinya. Sepertinya ini menjadi jawaban pertama atas
pertanyaan-pertanyaanku pada suasana kampung ini sejak kemarin. Antara
terkejut, kagum, dan senang seperti orang yang menemukan harta karun. Maaf, ini
bukan lebay, tetapi memang begitu kenyataannya membaca satu kisah sejarah yang
ternyata berkaitan dengan Indonesia, terutama suku Jawa. Aku merasa beruntung
sekali mendapat hostel di perkampungan bersejarah padahal awalnya kami mau
memesan hostel di daerah Little India. Aku tak sabar, kejutan apa lagi setelah
ini.
Sarapan sudah siap. Kami masuk ke ruang tamu hostel. Tiga pemuda
berambut pirang membuka peta Bali memakai komputer yang disediakan gratis oleh
hostel. Salah seorang menyebut Kuta. Sepertinnya mereka mau check out dan merencanakan ke Bali. “Do
you wanna go to Bali?” sapaku
“Yes.”
“I’m Indonesian.”
“Oh ya? We just from Thailand and wanna go to Bali after this.” Satu-satunya laki-laki di antara mereka menjawab dengan ramah dan salah satu yang lain mengatakan punya teman orang Indonesia.
Sejak kemarin aku memang sering bertemu dengan turis bule
yang umumnya anak muda, tapi belum bertemu dengan orang Melayu apalagi
Indonesia. Padahal, Singapura salah satu negara terdekat dengan Indonesia. Aku
jadi ingat para pelayar legendaris dari barat yang mengarungi samudra hingga ke
benua-benua lain. Mereka berani menantang ganasnya samudra dan ketidaktahuan
pada tanah yang akan mereka tapak demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
menyebarkan pengaruh, meski sering berakhir pada imprealisme. Barangkali bule
muda-bule muda ini mewarisi semangat berlayar dari kakek moyang mereka.Lamunanku terpecahkan oleh obrolan beberapa orang dengan
aksen yang sangat kukenal
“Kalau kalian mau tahu Jepang. Tanya ini lho yang pernah ke Jepang. Kalau saya baru dari Hongkong.” Ucap seorang bapak-bapak muda kepada anak-anak muda berwajah Indonesia. Hei? Orang Indonesiakah?
Kebetulan beliau juga sedang duduk di ruang tamu menyeduh teh hangatnya. “Bisa bahasa Indonesia ya?” sapaku
“Lhah saya orang Indonesia. Saya orang Banjar.”
Serasa bertemu teman, kami lalu mengobrol panjang. Namanya
Bang Fauzan. Sama seperti dua mas-mas tadi pagi, beliau juga sedang ada urusan
bisnis. Mendengarkan perjalanan bisnisnya sejak kuliah seperti sedang mengikuti
sebuah talk show interaktif.
Singapura seperti sudah menjadi kunjungan yang biasa baginya. Afrika Selatan,
Hongkong, Malaysia, dan entahlah aku sampai lupa di mana lagi negara yang sudah
pernah dikunjunginya. Tak hanya luar negeri, pelosok Indonesia pun pernah
beliau sambangi. Semua untuk urusan bisnis. Memang benar-benar berjiwa bisnis
abang satu ini. Kami berdua kagum pada perjalanannya bisnisnya yang selalu
dilandasi nilai-nilai Islam.
Puas mengobrol, kami mulai bergerak ke tujuan masing-masing.
Kemarin malam saat berjalan-jalan, kami melihat sebuah bangunan bertuliskan
Malay Herritage Centre. Waktu di Jakarta kami memang melihat peta museum itu
tidak jauh dari hostel, tetapi tak menyangka ternyata sedekat itu. Sebenarnya
ini tidak masuk list tujuan, tetapi
karena dekat kami datangi juga di pagi yang cerah ini. Children Little Museum
yang berada di depan hostel masuk dalam list,
tapi belum buka jadi kami berencana nanti sore akan ke tempat itu.
Bangunan bercat kuning ini hanya berada di sisi timur laut
Masjid Sultan. Aku bingung, mengapa ada museum berhubungan dengan Malaysia di
Singapura? Ya, barangkali karena Singapura mempunyai beberapa etnis mayoritas
di sini, jadi perlu ada bangunan yang menunjukkan pusatnya salah satu etnis,
seperti Little India, China Town, dan yang akan kudatangi adalah Malay
Herritage Centre. Harga tiket masuknya $6 untuk umum dan $4 untuk student.
Lucunya saat mbak-mbak bagian pemesanan tiket bertanya padaku apakah aku
student atau pekerja, Miss Lisfah menjawab aku student dan dia worker. Apa dia
lupa aku baru sebulan lalu lulus kuliah profesi? Aku sok menawarkan padanya
kartu bukti bahwa aku pelajar yang padahal aku hanya punya kartu
perpustakaannya, “Should I show my
student card?” sambil merogoh dompet. “Oh,
no.” jawabnya. Aku beruntung sekali pagi ini karena telah hemat $2. Biar
sudah bukan pelajar, aku paling suka harga pelajar.
 |
| MHC tahun 1970an |
Museum menyediakan guide
gratis berbahasa Inggris. Jika mau, kami bisa ikut bersama turis lain untuk
mendengarkan penjelasannya. Demi kebebasan mengeksplore museum, kami memilih
melihat-lihat sendiri. “Adek mau lihat-lihat sendiri atau ikut rombongan?”
tanya seorang petugas museum yang lagi-lagi langsung memakai bahasa Melayu.
Kami jelaskan pilihan kami. Beliau bertanya asal rumah kami. Saat kami jawab
asal secara detail, beliau menunjukkan ekspresi senang, “Oh, kakek saya orang
Banten. Tapi saya lahir di sini dan jadi warga sini.” Wah, kami jadi mengobrol
sebentar dengannya. Aku senang museum memperbolehkan memfoto asal tidak memakai
flash dan tidak merekam.
Display pertama museum berhubungan dengan perairan Singapura
dan yang pertama kulihat adalah peta Nusantara dengan peta Indonesia yang
sangat luas. Wow, betapa terkejutnya aku ada peta Indonesia di sini dengan
Singapura yang sangat kecil. Oh, sebentar-sebentar…aku amati lagi dengan lebih
seksama jalur-jalur kapal yang melintasi antar pulau. Ya ampun, aku baru
mengerti bahwa yang dimaksud Nusantara itu tidak hanya Indonesia, tetapi juga
Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, dan Filipina. Astaga.. belajar apa saja
aku ini? Mengapa baru sadar luas wilayah nusantara. Aku hanya ingat sumpah
palapa yang dikatakan Patih Gajah Mada yang intinya tidak akan bersenang-senang
sebelum menyatukan nusantara. Oh, ternyata seluas ini kerajaan Majapahit kala
itu. Luar biasa sekali. Selama ini aku hanya mengira Singapura dulu bagian dari kerajaan
Sriwijaya, sang penguasa laut.
Masuk ke bagian ruang tengah, aku semakin terkejut mengetahui
foto-foto nenek moyang orang Singapura. Orang Minang, Jawa, Bali, Banjar,
Melayu bagian Riau, Johor dan Melaka adalah suku-suku perintis masyarakat
Singapura. Benda-benda peninggalan mereka pun sangat mirip dengan tradisi
Indonesia. Kapal Pinisi khas orang Bugis didisplay beserta kapal-kapal yang
pernah menuju Singapura. Pinisi terlihat yang paling besar dan modern dibanding
lainnya. Ah, aku tahu sekarang mengapa kawasan ini disebut Kampung Bugis. Rasanya
campur aduk. Antara bangga terhadap suku-suku Indonesia yang membangun
Singapura di awal terbentuknya, haru karena ternyata Indonesia dan Singapura
seperti saudara sedarah dan sebangsa, bersyukur karena aku diarahkan penghuni
langit untuk belajar di tempat ini, dan menyayangkan orang Indonesia yang tidak
banyak tahu tentang ini.
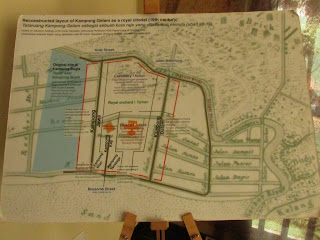 |
| Peta daerah Kampung Glam |
 |
| bawah kanan: parutan "kuda-kudaan" seperti yang aku lihat di Papua |
 |
| yang seperti ini di Indonesia masih banyak |
 |
| Pinisi |
 |
| Leluhur Melayu di Singapura |
 |
| Ibu Kita Kartini jadi cover majalah |
Malay Herritage Centre, pusat kebudayaan melayu bukan Malaysia
seperti yang aku pikir di awal. Bangungan ini kecil, tapi telah membuka banyak
cerita sejarah yang sangat berarti. Hem… sepertinya harus ada pembenahan materi
pelajaran sejarah di sekolah. Ayo, ketahuilah bahwa kita adalah bangsa yang
besar, bangsa yang mampu membangun peradaban di wilayah yang sangat luas tanpa
ada unsur imprealisme. Maka, kita harus ingat pesan Bung Karno, “Jangan
sekali-kali melupakan sejarah!”
“It’s a great museum.” Komentarku pada petugas museum tadi.
Atas informasi yang sangat edukatif dan display yang cukup
menarik aku beri nilai 80 untuk Malay Herritage Centre
Nyasar 3
Lanjut tujuan kedua kami berjalan-jalan di Haji Lane di
sebelah timur museum. Dulu, di sepanjang kampung ini dipakai untuk tempat
transit para jemaah haji dari Hindia
Belanda yang akan ke Mekah. Bangunan-bangunan kuno mirip dengan bangunan di
Bussorah St masih berdiri kokoh di sepanjang jalan. Hanya saja, unsur asli dan kuno
sudah hilang dari bangunan-bangunan ini karena mural bergaya modern dan
aksen-aksen pemanis toko telah mewarnai kampung ini. Kebanyakan toko di sini
menjual baju bergaya modern maupun tradisional. Bahkan saya bisa menemukan
penjual baju batik di sini. Beberapa toko juga memasang papan bertuliskan
“BAR”. Bar memang hal yang biasa di Singapura. Padahal awalnya aku pikir di
sini menjual benda-benda berhubungan dengan keislaman sesuai dengan namanya.
Bagi penyuka shoping dan selfie di sini tempat yang bisa memuaskan mereka.
Kalau aku lebih suka dengan bangunan kuno yang masih terlihat keasliannya. Di
dekat Haji Lane ini ada Bali Lane yang lagi-lagi banyak Bar. Sayang sekali
tidak ada toko atau aksen yang berhubungan dengan tradisi Bali di sini.
 | |
| Salah satu mural di Haji Lane |
Sebenarnya aku berencana ke National Intitut of Education,
tetapi karena jaraknya jauh aku membatalkannya karena belum punya teman yang
berkuliah atau bekerja di sana. Kalaupun ke sana aku hanya akan melihat
bangunan. Aku memutuskan untuk menemani Miss Lisfah ke Patlight School, sebuah
sekolah untuk anak-anak autis. Selain ingin kepoin
pelayanan sebuah sekolah untuk siswa autis, dia juga ingin mendaftar pelatihan
tentang kurikulum yang diselenggarakan autism
centre.
Aku merekam perjalanan saat di dalam bus. Aku percayakan
tujuan halte pada Miss Lisfah, apalagi ini destinasi pilihannya. Sambil membaca sreen shoot jalur bus di HP nya, dia
mengawasi satu per satu halte tempat bus berhenti. “Eh, sebentar. Jangan-jangan
kita kelewatan?” selanya
“Hah? Kelewatan?” aku pasang wajah bingung sambil berhenti
merekam
Kami lalu beranjak dari kursi dan dia bertanya pada sopir
bus. Eng ing eeeng…ternyata kami kelewatan satu halte. Kami disarankan sopir
untuk menyeberang dan menunggu bus. Sayangnya sistemnya tidak bisa transit
seperti di Trans Jakarta, sehingga kami harus mengetap kartu lagi. Ingat,
nyasar=boros, jadi Tips menggembel no 6 adalah awasi baik-baik tujuan
perjalanan saat di transportasi umum. Jangan melamun apalagi ketiduran.
Saat memberikan penjelasan tentang maksud kedatangan kami
kepada petugas kantor receptionist, seorang ibu-ibu muda berwajah oriental
masuk ke ruangan. “Whose wallet is this?”
sambil menunjuk dompet ungu tergeletak di kursi. “Hei, itu dompetmu.”
Tanganku menyenggol lengan Miss Lisfah. Ibu-ibu muda yang ternyata ketua
yayasan itu terlihat deg-degan melihat dompet tergeletak. Mereka berdua lalu
megobrol soal pendidikan untuk anak-anak autis. Satu perkataan yang sangat
mengena dari ibu-ibu itu adalah, “Kami tidak menyelenggarakan kunjungan atau
pelatihan untuk satu dua orang. Kalau mau ajaklah teman-temanmu, agar yang
mendapatkan ilmu itu tidak hanya sedikit orang. Atau kalau kamu ingin mengikuti
seminar atau pelatihan yang kami adakan, kamu harus membagi ilmu ke teman-temanmu
saat pulang. Ajaklah teman-temanmu untuk sukses bersama.”
Sayangnya, karena belum ada surat masuk ke sekolah itu, maka
informasi yang diberikan hanya terbatas dan kami tidak diperbolehkan untuk
mengelilingi kompleks sekolah.
 |
| Jalan raya di depan Patlight School yang sepi |
Aku beri nilai 65 untuk kunjungan ke Patlight School karena
terbatasnya informasi yang kami dapat.
Perjalanan pulang di bus menjadi amat sangat kaku sekali
karena ada pertengkaran kecil soal kebiasaan lupanya Miss Lisfah yang terulang
saat di Patlight School. Ini akan merepotkan kalau berlanjut lama karena kami
hanya berdua. Tiba-tiba bahuku ditepuknya. Kami lalu turun di seberang jalan
sebuah Majid berwarna biru. Ah, aku tahu itu! Itu adalah salah satu masjid yang
terkenal di Singapura yang bernama Masjid Malabar. Kami sekalian sholat Zuhur
dan Ashar di masjid yang tembok luar sampai kubahnya di tempeli ribuan keramik
ini.
Beberapa orang yang kutemukan di dalam masjid berwajah India
karena memang masjid ini didirikan oleh organisasi India. Suasananya terasa
India, berbeda dengan Masjid Sultan yang terasa Melayu. Lokasinya yang tidak
berada di daerah penginapan atau destinasi wisata membuatnya terasa lebih sepi
dan memang cerita sejarahnya tidak sepanjang Masjid Sultan.
 |
 |
| Siswa-siswa madrasah pulang sekolah |
Kunjungan singkat di Masjid Malabar ini kuberi nilai 75
Perjalanan yang selanjutnya ke tempat yang paling iconic di
Singapura. Mana lagi kalau bukan patung Singa muntah. Kami melanjutkan
perjalanan dengan naik bus sekali jalan. Kami melewati banyak taman yang
cantik, bersih, dan modern di sepanjang perjalanan. Pantas saja Singapura ini
disebut memiliki lahan terbuka hijau yang lebih banyak daripada Jakarta.
Awalnya kupikir semua tempat di sini sudah berdiri bangunan mewah, tetapi
ternyata tidak begitu. Hampir tidak ada rumah yang berdiri di sini, semua
penduduk sudah terkumpul dalam rumah susun atau apartemen. Toko, rumah makan,
dan gedung-gedung perkantoran rata-rata juga menjulang ke atas bukan ke
samping. Itulah yang menyebabkan masih banyak lahan yang digunakan untuk taman.
Uniknya, aku sama sekali tak melihat tanah kosong yang bisa
diinjak di sini karena setiap tanah pasti ditumbuhi rumput, sedangkan yang lain
sudah dijadikan taman atau dipaving. Jadi aku bisa menjamin alas sepatu kita
tidak akan tekena tanah becek. Aku juga sama sekali tak melihat PKL atau pedagang-pedagang
kecil di sepanjang trotoar. Tiba-tiba aku teringat Batagor dan Siomay 5000-an
yang enak di trotoar Jakarta. Yah, semua ada kekurangan dan kelebihannya.
Kami turun di Marina Bay Stn. Ternyata dari situ kami harus
mengelilingi “emperan” gedung-gedung mewah untuk sampai di icon itu. Kami
berjalan setengah berlari karena langit gelap sekali dan terasa beberapa detik
tetesan kecil dari langit mendarat di tangan. Saat sampai di sana, banyak turis
berbagai macam etnis berfoto-foto di sekitarnya. Kalau bukan karena ini icon
yang telah mendunia, sebenarnya aku merasa biasa saja dengan tujuan ke Merlion.
Menurutku masih lebih keren Monas. Mungkin kalau ada informasi tentang legenda
Singa berekor ikan ini (yang katanya berhubungan dengan pangeran Palembang), sejarah
tentang daerah ini, pertunjukan seni, atau jajanan rakyat sepertinya akan lebih
menarik. Sayangnya ini bukan Malioboro yang ramai dengan musisi jalanan atau
jajanan tradisional. Ini Marina Bay yang penuh dengan gedung modern berkelas internasional
mulai dari kafe hingga BRI.
 |
| Rasa-rasanya langit siap menerkamku |
Ini Video
Ini juga video
“Do you want me to take
your picture?” tawar
Miss Lisfah ke beberapa pengunjung yang tidak bawa tongsis. Pertanyaan ini
memang biasa ditawarkan orang ke tiap turis yang terlihat pengen berfoto tapi
apadaya tak bawa tongsis, seperti kami berdua yang tadi pagi ditawarkan seorang
bapak untuk berfoto di Haji Lane.
“Aku merasa kunjungan kita tadi pagi lebih menarik
dibandingkan ini.” Komentar Miss Lisfah.
 Jalan-jalan ke patung Singa muntah atau bahasa
internasionalnya Merlion ini kuberi nilai 70. Kalau di masa depan muntahnya tidak ke
depan tapi ke atas mungkin bisa kuberi tambahan nilai 5 poin.
Jalan-jalan ke patung Singa muntah atau bahasa
internasionalnya Merlion ini kuberi nilai 70. Kalau di masa depan muntahnya tidak ke
depan tapi ke atas mungkin bisa kuberi tambahan nilai 5 poin.
Kami tidak menghabiskan sore hingga melihat esplanade di sana
karena khawatir akan hujan, perut sudah sangat lapar, dan kaki sudah gempor.
Lebih baik kami pulang mengisi saldo kartu MRT lalu pulang dan makan malam di
rumah makan kemarin yang pasti harganya jauh lebih murah dibanding sekitar
Marina Bay. Kami harus ke stasiun untuk meng top up kartu dan minimal tambahan
saldonya sebanyak $10. Tidak seperti stasiun di Jakarta, stasiun bawah tanah di
sini sudah seperti Mall yang penuh dengan penjual. Rasa-rasanya tidak ada
sejengkal tanahpun tersia-siakan.
Makan malam kali ini dengan Nasi Biryani. Sepertinya mirip
nasi goreng tapi berbumbu kari India. Aku sebernanya agak ragu saat memesan
nasi ini karena aku tidak begitu suka nasi (maaf bukan bermaksud sok gaya.
Hehe), tetapi karena Miss Lisfah ingin makan nasi jadi tidak mungkin kami makan
nasi sepiring berdua. Saat uncle menghidangkan sepiring nasi ini, ya ampuunnn
ini benar-benar porsi besar untukku. Bagiku ini bisa dimakan tiga orang. Nasi
dengan porsi besar dan bumbu rempah-rempah menyengat yang tak biasa membuatku
hanya mampu menghabiskan setengah nasinya. Aku merasa sayang sekali, apalagi harganya
lebih mahal dibanding Murtabak ($6,5).
“I’m sorry uncle I can’t clean my plate. It’s too much for me.” Dari sedih menjadi merasa bersalah karena menyia-nyiakan makanan.
“Oh. Mau dibungkuskah? Kalau mau saya bungkus.” Akhirnya nasiku dibungkus dan diberi kuah rempah lagi. Baiknya uncle.
Perjalanan hari ini selesai. Kami batal ke Children Little
Museum karena sudah tutup. Malam ini di kamar kami ada tiga mahasiswa Indonesia
yang menginap menggantikan bule-bule yang kemarin mendominasi. Besok adalah
acara puncak yaitu bertemu dengan guru-guru. Aku penasaran seperti apakah
mereka.
Bersambung lagi...















